ABSTRAK
Komitmen terhadap kesetaraan, keberagaman, dan inklusi (EDI) dapat ditemukan sebagai pernyataan di situs web sebagian besar universitas di Inggris. Seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki pendidikan tinggi—yang mencakup lebih dari 50% dari mahasiswa sarjana—wacana feminisasi pendidikan tinggi telah terlihat jelas dalam tanggapan media dan kebijakan selama lebih dari satu dekade. Tesis feminisasi ini mengasumsikan bahwa perempuan tidak hanya sekarang menjadi mayoritas secara numerik tetapi juga mengubah budaya sistem. Dari perspektif EDI, oleh karena itu kita mungkin berasumsi bahwa dalam kaitannya dengan mahasiswa perempuan, setidaknya, hanya sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, ada bukti untuk mempertanyakan tesis feminisasi. Artikel ini berkontribusi pada bidang tersebut dengan memberikan perhatian pada ‘suara’ mahasiswa sebagai strategi kesetaraan dan inklusi yang berharga, selain mengeksplorasi bagaimana inklusi dapat dipahami dalam konteks elit. Secara metodologis inovatif, artikel ini menganalisis pers mahasiswa Universitas Cambridge pada tahun ketika lokakarya persetujuan seksual diperkenalkan. Mengacu pada kerangka teoritis ‘ruang’, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana mahasiswa menggunakan pers mahasiswa sebagai ‘ruang’ untuk menarik perhatian pada ruang ‘representasional’ mahasiswa perempuan dan penggabungan ruang tertentu dengan tubuh tertentu. Artikel ini akan mengemukakan argumen dan menyajikan bukti untuk menunjukkan bahwa kritik dari ‘dalam’ menantang gagasan tentang kesetaraan, keberagaman, dan inklusi.
1 Pendahuluan
Komitmen terhadap kesetaraan, keberagaman, dan inklusi (EDI) dapat ditemukan sebagai pernyataan di situs web sebagian besar universitas di Inggris (Koutsouris et al. 2022 ). Seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki pendidikan tinggi—mencakup lebih dari 50% dari mahasiswa sarjana—wacana feminisasi pendidikan tinggi telah terlihat jelas dalam tanggapan media dan kebijakan selama lebih dari satu dekade. Tesis feminisasi ini berasumsi bahwa perempuan tidak hanya sekarang menjadi mayoritas secara numerik tetapi juga mengubah budaya sistem (Leathwood dan Read 2008 ). Oleh karena itu, dari perspektif EDI, kita mungkin berasumsi bahwa setidaknya terkait dengan mahasiswa perempuan, hanya sedikit pekerjaan yang harus dilakukan.
Akan tetapi, ada bukti yang mempertanyakan tesis feminisasi dan dengan demikian menantang gagasan tentang kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas. Secara definisi, kesetaraan berkaitan dengan hak dan kesempatan yang sama, dengan ekuitas memperhitungkan bahwa orang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya karena sistem penindasan dan hak istimewa dan memastikan kesenjangan ini seimbang. Keberagaman mengacu pada komunitas atau organisasi yang beragam di mana berbagai karakteristik sosial dan budaya ada. Akhirnya, inklusi mengacu pada membawa individu dan kelompok yang secara historis dan/atau saat ini kurang terwakili atau terpinggirkan ke dalam proses, aktivitas, dan pengambilan keputusan, bersama dengan menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai (Aiston 2024 ; Lam et al. 2024 ). Seperti yang ditulis Ahmed, ‘Pekerjaan keberagaman dapat berbentuk deskripsi: ia dapat menggambarkan efek dari menghuni ruang institusional yang tidak memberi Anda tempat tinggal’ (Ahmed 2012 , hlm. 176).
Penelitian yang berkaitan dengan posisi, status, dan pengalaman dosen perempuan sangat luas, namun, penelitian yang berkaitan dengan mahasiswi sebagian besar berfokus pada dua area utama: yang terpenting adalah kurangnya representasi mereka dalam mata pelajaran STEM dan pelecehan seksual. Artikel ini berkontribusi pada bidang tersebut dengan memberikan perhatian pada ‘suara’ mahasiswa sebagai strategi kesetaraan dan inklusi yang berharga (McLeod 2011 ), selain secara khusus mengeksplorasi bagaimana inklusi/inklusivitas dapat dipahami dalam konteks elit (Koutsouris et al. 2022 ). Di sini penggunaan ‘elit’ mengacu pada universitas-universitas tersebut, baik di Inggris maupun internasional, yang diakui sebagai institusi paling bergengsi yang memiliki peringkat tinggi di beberapa peringkat dunia, sebagian besar intensif penelitian, terhubung dengan elit nonakademis lainnya dan sering dianggap ‘eksklusif’, yang merupakan kebalikan dari inklusif (Bhopal dan Myers, 2022; Koutsouris et al. 2022 ). Dengan fokus pada Universitas Cambridge—universitas Inggris terakhir yang memberikan keanggotaan penuh kepada perempuan pada tahun 1948—sebagai studi kasus universitas elit global, artikel ini menganalisis agensi mahasiswa dari ‘dalam’ untuk mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual serta norma gender. Secara metodologis inovatif, artikel ini menganalisis pers mahasiswa Universitas Cambridge pada tahun ketika lokakarya persetujuan seksual diperkenalkan (2015), yang ditetapkan dalam konteks yang lebih luas di mana secara bersamaan kekhawatiran tentang ‘lompatan rekor’ penerimaan mahasiswa perempuan di universitas dan prestasi rendah pemuda di pendidikan tinggi di Inggris, disandingkan dengan meningkatnya kekhawatiran internasional seputar pelecehan dan kekerasan seksual terhadap mahasiswa perempuan.
Mengacu pada kerangka teoritis ‘ruang’, khususnya karya Lefebvre ( 1991 ) dan Puwar ( 2004 ), artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana mahasiswa menggunakan pers mahasiswa sebagai ‘ruang’ untuk menarik perhatian pada ruang ‘representasional’ mahasiswi (Lefebvre 1991 ) dan penggabungan ruang-ruang tertentu dengan tubuh-tubuh tertentu (Puwar 2004 ). Artikel ini akan berargumen dan menyajikan bukti untuk menunjukkan bahwa kritik dari ‘dalam’ menantang gagasan tentang kesetaraan, keberagaman, dan inklusi.
Artikel ini terdiri dari beberapa bagian berikut: tinjauan pustaka; pembahasan konsep ‘ruang’ sebagai kerangka teoritis; pers mahasiswa sebagai pendekatan metodologis; penyajian dan analisis data; dan terakhir, kesimpulan.
2 Literatur Sebelumnya
Penelitian sebelumnya telah menantang tesis feminisasi. Meskipun perempuan terwakili dengan baik—pada tingkat agregat —sebagai mahasiswa sarjana di Global Utara, perempuan “gagal” untuk bergerak melalui hierarki pendidikan dan mencapai jabatan paling senior dan posisi kepemimpinan di akademi global (Fitzgerald 2014 ; Morley 2014 ). Penelitian yang berkaitan dengan posisi, status, dan pengalaman perempuan sebagai akademisi sangat luas.
Namun, penelitian yang terkait dengan status, posisi, dan pengalaman perempuan sebagai pelajar, sebagian besar berfokus pada dua area utama: pertama, kurangnya representasi mereka dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dan kedua, pelecehan seksual terhadap pelajar perempuan. Meskipun ada ‘pembalikan’ dalam ketidaksetaraan gender dalam kaitannya dengan partisipasi, pilihan mata pelajaran masih sangat bergantung pada gender (Verdugo-Castro et. al., 2022; Vincent-Lancrin 2008 ,), bahkan dalam disiplin STEM itu sendiri (Barnard et al. 2012 ; Watt et al. 1998 ). Penelitian menunjukkan bahwa siswi di bidang STEM diposisikan sebagai ‘istimewa’ dan ‘berbeda’ (Powell et al. 2012 ; Rodd and Bartholomew 2006 ) dan bahwa mereka mengalami lingkungan yang sangat maskulin—’iklim yang dingin’ (Du 2006 ; Erwin and Maurutto 1998 ; Lynch and Nowosenetz 2009 ; Slattery et al. 2023 ). Ancaman stereotip, identitas diri, dan faktor efikasi diri dalam keraguan yang diungkapkan perempuan tentang kemampuan dan rasa memiliki mereka dalam mata pelajaran STEM (Ahlqivist et al. 2013 ; Fisher et al. 2020 ; García Villa and González y González 2014 ).
Fenomena global pelecehan dan kekerasan seksual terhadap mahasiswi juga menjadi bidang penelitian yang penting (Barnacle et al. 2022 ; Bondestam dan Lundqvist 2020 ; Lombardo dan Bustelo 2021 ; List 2017 ; Paoletti et al. 2021 ; Phipps 2017 ; Towl dan Walker 2019 ). Bukti dari Inggris (National Union of Students 2010 ; Universities UK 2016) ), Komisi Hak Asasi Manusia Australia 2016 ), Amerika Serikat (Fedina et al. 2016 ; Krebs et al. 2016 ) dan Kanada (CCI Research Inc. 2019 ; Lee dan Wong 2019 ) secara khusus telah menarik perhatian pada endemik ini, dan ketidakcukupan kebijakan dan praktik universitas untuk menangani masalah ini. Misogini, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan telah dipadukan dengan ‘budaya laki-laki’ dan ‘kelaki-lakian’, sehingga menghasilkan penelitian yang berupaya menganalisis hegemoni maskulinitas dan perlawanan dalam pendidikan tinggi (Dempster 2009 ; Dempster 2011 ; Jackson dan Sundaram 2020 ; Jeffries 2019 ). Studi ini berkontribusi pada bidang ini dengan memberikan perhatian pada ‘suara’ mahasiswa, melalui pers mahasiswa, sebagai strategi kesetaraan dan inklusi yang berharga (McLeod 2011 ) untuk menganalisis pengalaman mahasiswa perempuan di Universitas Cambridge.
2.1 Konsep ‘Ruang’: Kerangka Teoritis
Karya Lefebvre yang ditulis pada tahun 1974 mengenai ruang representasi , yaitu ruang yang dijalani dan dirasakan, diawali dengan pernyataan berikut:
![]()
Lefebvre mengajukan tesis ruang ‘sosial’ sebagai ‘produk sosial’, dengan menyatakan bahwa ruang tersebut ‘…juga merupakan alat kontrol, dan karenanya dominasi, kekuasaan’ (Lefebvre 1991 , hlm. 26). Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana para sarjana feminis dalam beberapa dekade terakhir telah meneruskan ide-idenya. Misalnya, pembahasan Lefebvre tentang hubungan produksi , yaitu pembagian kerja dan organisasinya dalam bentuk fungsi sosial hierarkis (lihat Lefebvre 1991 , hlm. 32) secara teoritis membingkai analisis ruang publik/pribadi di Inggris Victoria. Perempuan dibatasi pada ruang aman di rumah, sementara laki-laki bergerak bebas melalui kota-kota industri untuk bekerja dan bersantai. Baru-baru ini, para sarjana telah bergerak melampaui dualitas publik/pribadi dan mengonseptualisasi ulang ruang gender di sepanjang sebuah kontinum.
Karya Lefebvre khususnya telah memengaruhi ahli geografi manusia feminis sejak akhir tahun 1970-an dan mendukung pengembangan konseptualisasi ‘ruang gender’:
![]()
Karya penting Doreen Massey ( 1994 ) mengeksplorasi bagaimana ruang dan tempat terhubung dengan gender dan konstruksi geografis hubungan gender. Ahli geografi feminis telah menganalisis posisi perempuan di kota dan bagaimana perempuan dan laki-laki mengalami ruang secara berbeda. Misalnya, harapan spasial tentang bagaimana perempuan akan bergerak melalui ruang kota, mengambil bagian dalam pasar tenaga kerja dan berpartisipasi dalam sistem sosial dan politik yang diciptakan oleh laki-laki: ‘Dalam masyarakat Barat, laki-laki secara tradisional telah menggunakan kekuatan sosial dan ekonomi terbesar dan telah memengaruhi ruang di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka’ (Doan 2010 , hlm. 299).
Sejarawan juga semakin berupaya memahami bagaimana lingkungan, ‘bangunan’ dan lainnya, lingkungan arsitektur, lanskap, dan ‘tempat’ dan ‘ruang’ konseptual (istilah-istilah tersebut tidak sinonim) telah memengaruhi sifat dan cakupan kekuatan politik, produksi budaya, dan pengalaman sosial (Beebe et al. 2012 , hlm. 523). Berbeda dengan konseptualisasi ‘ruang’ sebagai ‘tempat’ geografis statis, ruang diposisikan ulang sebagai dinamis, dibangun, dan diperebutkan:
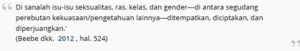
Dalam artikel ini, Universitas dikonseptualisasikan sebagai ruang (sosial), khususnya mengacu pada gagasan ruang representasional. Ruang representasional adalah tempat makna dibuat dari ‘simbolisme kompleks’ yang diambil dari pengalaman ruang fisik ‘yang dijalani’ sehari-hari dan makna yang kita buat darinya, melalui ‘konseptualisasi’ yang kita tetapkan pada ruang ‘yang dijalani’ tersebut. Dalam kata-kata Lefevbre, ruang representasional ‘dijalani’ melalui gambar dan simbol terkait dan karenanya menjadi ruang ‘penghuni’ dan ‘pengguna’ (Lefebvre 1991 , hlm. 528).
Analisis Nirmal Puwar ( 2004 ) tentang bagaimana tubuh tertentu secara alami berhak atas ruang tertentu, sementara yang lain tidak, sangat relevan dengan studi tentang mahasiswi di Universitas Cambridge. Secara historis, Universitas Cambridge adalah ruang (sosial) laki-laki yang memberikan keuntungan bagi laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. 1 Seperti disebutkan, Cambridge adalah universitas terakhir di Inggris yang mengizinkan perempuan untuk menjadi anggota penuh ruang (sosial) ini dan lulus sebagai setara dengan sesama mahasiswa laki-laki. Upaya sebelumnya untuk menerima mahasiswa perempuan secara penuh mengakibatkan patung perempuan yang dipenggal kepalanya dilemparkan ke Girton, sebuah perguruan tinggi khusus perempuan yang didirikan pada tahun 1869. Perempuan diizinkan untuk memasuki sejumlah perguruan tinggi laki-laki sejak tahun 1972, dengan Magdelene menjadi perguruan tinggi laki-laki terakhir yang menerima perempuan pada tahun 1988, yang mendorong para mahasiswa untuk berprosesi melalui jalan-jalan Cambridge dengan peti mati, mengenakan ban lengan hitam, untuk meratapi ‘kematian’ perguruan tinggi mereka. Penelitian Puwar bertanya: apa yang terjadi ketika tubuh-tubuh itu, yang tidak diharapkan untuk menempati tempat-tempat tertentu, melakukannya? Apa saja syarat-syarat koeksistensi? Mengacu pada teorinya tentang keterkaitan ruang-ruang tertentu dengan tubuh-tubuh tertentu, artikel ini merefleksikan sejauh mana mahasiswi di Universitas Cambridge dapat dianggap sebagai ‘penyerbu ruang’, yaitu, pelintas batas, bukan dari norma somatik.
3 Pers Mahasiswa: Pendekatan Metodologis
Penelitian tentang posisi, status, dan pengalaman mahasiswi sebagian besar menggunakan data statistik, survei, dan wawancara. Melanjutkan penelitian historis Aiston ( 2006 ) sebelumnya tentang representasi mahasiswi universitas dalam pers mahasiswa pasca-Perang Dunia Kedua, artikel ini berupaya mempertimbangkan sejauh mana mahasiswi di Cambridge dapat dianggap sebagai penyerbu ruang dengan menganalisis pers mahasiswa Universitas Cambridge. Dalam sejarah pendidikan tinggi perempuan, para sejarawan hanya mengalihkan perhatian mereka secara sekilas ke analisis sumber yang menghasilkan wawasan substansial tentang hubungan gender dalam kehidupan akademis dan wacana serta citra yang berusaha mendefinisikan mahasiswi universitas. Penelitian Aiston ( 2006 ) berpendapat bahwa mahasiswa laki-laki ‘di rumah’ dalam pendidikan tinggi, sementara mahasiswi universitas ‘tidak pada tempatnya’. Demikian pula, peneliti kontemporer belum memanfaatkan pers mahasiswa sebagai sarana untuk menganalisis pengalaman mahasiswi di abad ke-21. Oleh karena itu, penelitian ini untuk pertama kalinya menyajikan analisis pers mahasiswa.
Universitas Cambridge memiliki tiga surat kabar mahasiswa; Varsity , sebuah surat kabar independen, pertama kali diterbitkan pada tahun 1947; The Cambridge Student Newspaper (TCS), yang diproduksi oleh Serikat Mahasiswa Universitas Cambridge (didirikan pada tahun 1999), dan The Tab , sekarang situs media nasional, tetapi awalnya didirikan di Cambridge pada tahun 2009. Ketiga surat kabar tersebut dibaca selama satu tahun akademik: 2014–2015, tahun di mana lokakarya persetujuan seksual diperkenalkan untuk pertama kalinya di Universitas. Salinan lunak dari edisi kertas Varisty dan TCS diarsipkan di situs web surat kabar tersebut. Cambridge Tab —sebagai surat kabar daring—berisi bagian arsip di mana setiap artikel individual dicantumkan setiap bulan. Semua artikel, komentar, gambar yang berkaitan dengan gender—dan variabel interseksional utama lainnya, (misalnya kelas sosial ekonomi, etnis, seksualitas)—dicari untuk mengenali pentingnya interseksionalitas sebagai komponen penelitian EDI.
Analisis ini didasarkan pada studi Gasman ( 2007 ) tentang liputan media terhadap perguruan tinggi kulit hitam di Amerika Serikat, dan penggunaan analisis media kualitatif tiga tahap milik Altheide ( 1996 ).
- Tahap 1 dari analisis membingkai apa yang dibahas dan bagaimana cara pembahasannya
- Tahap 2 analisis berkaitan dengan identifikasi tema , yaitu ide-ide dominan yang muncul dalam diskusi; dimensi pesan ini penting untuk pengembangan ‘kerangka masalah’ (Altheide dan Schneider 2013 );
- Tahap 3 analisis mengeksplorasi wacana —kata-kata, gambar, frasa—dengan menekankan isu-isu yang diwakili.
Di sini, Richardson ( 2007 ) tentang wacana surat kabar sangat membantu. Misalnya, bahasa selalu aktif; wartawan menggunakan bahasa untuk memberi tahu kita tentang suatu peristiwa, untuk mengungkap kesalahan, atau untuk membela suatu hal. Selain itu, penggunaan bahasa memiliki kekuatan:

Dan di sini kita dapat melihat pentingnya politik suara: ‘janji untuk memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili dan terpinggirkan telah menjadi andalan agenda emansipatoris dan radikal dalam praktik dan penelitian pendidikan’ (McLeod 2011 , hlm. 179). Seperti yang ditekankan McLeod, memberikan perhatian pada suara menandakan perhatian terhadap representasi dan pemberdayaan, dan sementara ada kritik terhadap politik suara, daya tarik suara sebagai strategi untuk mempromosikan pemberdayaan, inklusi, dan kesetaraan tetap kuat. Kesetaraan siswa sebagian besar difokuskan pada akses. Artikel ini menyajikan pandangan yang lebih luas tentang pengalaman siswa—dalam hal ini, perempuan—’untuk memahami dinamika ekuitas dan ketidaksetaraan yang kompleks dan tertanam secara historis’ (McLeod 2011) , hlm. 180).
Sebagaimana yang dikemukakan oleh para akademisi, pola liputan berita memengaruhi persepsi tentang isu apa yang penting, dan pola ini disebut sebagai agenda ‘media’ (Gasman 2007 ). Dengan mempertimbangkan konsep ‘penetapan agenda’, menjadi jelas bahwa agenda kesetaraan ditetapkan melalui media ini, sebagaimana akan dibahas di bawah ini.
4 Temuan
Dengan menggunakan ruang sebagai kerangka teoritis dan mengacu pada kerangka , tema, dan wacana Altheide , kerangka berikut diidentifikasi, yang mengklaim ruang representasional, ruang anak laki-laki, dan kekhawatiran seputar ruang aman. Contoh kerangka ini, dan tema serta wacana yang terkait dengan tiga kerangka utama ini sekarang akan dibahas.
4.1 Frame 1: Mengklaim Ruang Representasional
Pembingkaian surat kabar tersebut terhadap perempuan di Cambridge terwujud dalam edisi pertama berikut: sejauh mana perempuan terwakili secara spasial di dalam Universitas . Analisis terhadap tiga surat kabar mahasiswa memberikan wawasan tentang cara-cara perempuan terus berupaya mengklaim ruang representasi yang setara dalam berbagai cara, termasuk alokasi perguruan tinggi—di mana ditempatkan di perguruan tinggi dengan satu jenis kelamin digambarkan sebagai penolakan pengalaman universitas yang ‘penuh’; kesetaraan dalam olahraga (pada Prapaskah 2015, lomba perahu perempuan secara historis diberi penghargaan yang sama) dan masuk ke Klub Universitas (pada tahun 2015 perempuan tetap dikecualikan dari Klub Pitt yang terkenal khusus laki-laki)
Dalam kerangka ini, tema yang dominan adalah marginalisasi. ‘Ruang’ tersebut dibangun sebagai ruang di mana ‘mahasiswa perempuan masih dirugikan secara institusional’ (TCS, 22 Januari 2015, hlm. 14) Contoh-contoh berikut sekarang akan dipertimbangkan: berbicara di depan umum, disiplin/prestasi mata pelajaran, dan kepemimpinan mahasiswa.
Berbicara di depan umum
Setelah tuduhan seksisme oleh CUSU Women’s Campaign, kartu ujian Michaelmas untuk pembicara perempuan Union pada tahun ajaran baru 2014 telah meningkat menjadi 30% dari semua pembicara yang diundang. Pada masa Prapaskah 2014, hanya satu pembicara perempuan yang berbicara (Varsity, 3 Oktober 2014). Judul utama Tab pada saat itu berbunyi ‘Cambridge Union dikecam karena kurangnya perempuan dalam susunan acara Prapaskah’ (The Tab, 8 Januari 2014), yang menyampaikan rasa marah/murka terkait dengan ketidakhadiran perempuan dalam konteks bergengsi ini. Yang perlu diperhatikan secara khusus dalam peningkatan representasi pembicara perempuan untuk tahun ajaran baru 2014, adalah kedatangan Pussy Riot, band punk politik feminis Rusia. Wacana seputar acara tersebut menyampaikan rasa antisipasi dan kegembiraan, dikombinasikan dengan penilaian sensasional tentang kurangnya keberagaman secara historis: ‘Ini adalah berita yang sangat menggembirakan, terutama untuk lembaga lama yang cenderung mengundang pria tua kulit putih’ (Petugas Wanita CUSU, Varsity, 31 Oktober, hlm. 10) Demikian pula, TCS tampil dengan tajuk utama halaman depan ‘Tidak ada lagi pria tua kulit putih’? Pussy Riot akan mengunjungi Cambridge (TCS, 23 Oktober 2014, lihat juga The Tab, 22 Oktober 2014). Sementara kartu ucapan Paskah Serikat Pekerja dicatat menampilkan ‘sangat sedikit pembicara terkenal’, keberagaman pembicara kembali disorot:
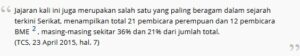
Disiplin Mata Kuliah dan Prestasi Akademik
Kesenjangan prestasi akademik antara mahasiswa pria dan wanita muncul tahun ini. TCS menganalisis statistik universitas yang menunjukkan mahasiswa pria memiliki prestasi yang lebih baik secara tidak proporsional dibandingkan mahasiswa wanita dalam mata kuliah tertentu. Di seluruh universitas, artikel tersebut melaporkan bahwa 29% mahasiswa pria memperoleh nilai tertinggi, dibandingkan dengan 20% mahasiswa wanita. Seorang mahasiswa wanita tahun ketiga berkomentar, ‘karena Universitas adalah institusi yang sangat konservatif, saya benar-benar ragu akan ada yang dilakukan untuk mengatasi hal ini’ (TCS, 19 Februari 2015, hlm. 3). Di sini, lihat bagaimana penggunaan ‘konservatif’ mengacu pada status quo yang dilestarikan/dilindungi; mahasiswa pria harus dilindungi dalam arti bahwa meskipun ada mahasiswa wanita, mereka tidak akan mengancam dominasi mahasiswa pria dalam hal hasil akademik.
Ketidakseimbangan gender yang signifikan pada siswa yang mempelajari mata pelajaran STEM pada tahun akademik ini juga dibahas. Merefleksikan rasio lamaran terhadap tawaran antara pria dan wanita yang mempelajari ilmu komputer, seorang penulis berkomentar: ‘Cambridge mungkin tidak secara langsung menciptakan batasan gender ini, namun tampaknya hanya ada sedikit upaya untuk memperbaikinya’ (TCS, 18 November 2014, hlm. 15). Kurangnya akademisi wanita dalam mata pelajaran STEM juga dicatat. Dalam serangkaian foto siswa yang memegang pernyataan tertulis tentang mengapa mereka membutuhkan feminisme, seorang siswi menulis ‘SAYA MEMBUTUHKAN FEMINISME KARENA 1/65 profesor matematika di Cambridge adalah wanita, dan itu kurang dari cukup’ (The Tab, Maret 2014).
Akan tetapi, tidak hanya dalam mata pelajaran STEM saja siswi perempuan dilaporkan mencari ruang representasional. Pada bulan Februari 2014, TCS mengomentari secara ekstensif tentang kesenjangan pencapaian gender dalam Tripos Sejarah. Ketika mempertanyakan mengapa kesenjangan ini mungkin terjadi, seorang penulis TCS merenungkan komponen-komponen utama esai yang baik, dengan mengutip demonstrasi rasa percaya diri sebagai hal yang paling utama. Penulis merenungkan bagaimana kata keterangan kualifikasi, misalnya, ‘mungkin’, ‘mungkin’ dilingkari dengan pena merah pada naskahnya sendiri yang ditandai, dan setelah membaca penelitian di bidang tersebut, menyimpulkan:
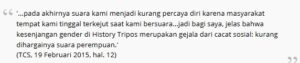
Ketidakadilan dalam jumlah juara pertama yang diberikan kepada perempuan muncul lagi ketika penulis Zadie Smith—lulusan Pembroke—mengomentari bagaimana ia merasa harus ‘menulis’, ‘berbicara’, dan ‘berdebat’ seperti laki-laki saat di Cambridge. Dengan membandingkan pengalaman Smith, Varsity mencatat saran bahwa mahasiswa perempuan perlu menulis dengan ‘agresif, keyakinan, dan bahasa yang lebih indah’ (Varsity, 17 Juni 2015, hlm. 20). Penjajaran agresi/indah di sini merupakan oposisi biner dalam hal norma kinerja gender. Implikasinya adalah bahwa mahasiswa perempuan perlu lebih seperti laki-laki, tetapi tidak kehilangan aspek feminin mereka.
Terkait hal ini, pelaporan mahasiswa tentang masalah ini sudah mendahului zamannya. Pada tahun 2024, sebuah laporan HEPI menyelidiki kesenjangan pemberian gelar berdasarkan gender; laki-laki lebih mungkin meraih gelar kelas satu di Universitas Oxford dan Cambridge, bahkan dalam disiplin ilmu yang mayoritas digeluti perempuan (misalnya Bahasa Inggris).
Kepemimpinan Siswa
Pada tahun ajaran ini, perempuan dilaporkan terus menjadi kelompok yang paling kurang terwakili dalam kepemimpinan ekstrakurikuler di Cambridge (Varsity, 28 November 2014). Melihat latar belakang presiden Cambridge Union Society, presiden Junior Common Room (JCR) dan editor dari tiga surat kabar, Varsity menemukan perbedaan yang signifikan. Dari semua posisi yang disurvei, 62% dipegang oleh laki-laki. Dari 29 JCR, hanya 11 yang dipimpin oleh presiden perempuan, yang mencakup kepemimpinan perempuan dari tiga perguruan tinggi khusus perempuan. Ini mewakili 31% JCR yang dipimpin oleh presiden perempuan. Terkait dengan Cambridge Union Society, hanya dua dari tujuh presiden dalam periode 3 tahun sebelumnya adalah perempuan. Kepala cabang Women, Class, Access dari Women’s Campaign CUSU dilaporkan berkomentar, ‘mungkin dengan melihat statistik ini kita harus ingat bahwa universitas ini awalnya tidak dirancang untuk perempuan’ (Varsity, 28 November 2014, hlm. 4). Di sini tampaknya ada penerimaan yang pasrah bahwa tujuan historis akan kembali ‘melestarikan’ yang mengakibatkan marginalisasi perempuan dan oleh karena itu kurangnya representasi mereka dalam badan-badan mahasiswa seperti ini. ‘Kita harus ingat’ tampaknya menunjukkan bahwa ada penyesalan bahwa perempuan perlu memperhitungkan bahwa mereka tidak termasuk di masa lalu sehingga tidak berharap untuk secara otomatis termasuk di masa sekarang atau masa depan.
Pada bulan Februari 2015, TCS melaporkan ‘kemarahan’ mahasiswa atas restrukturisasi JCR di Churchill College, yang menyebabkan pencopotan Pejabat Wanita dari komite, situasi yang kemudian dibatalkan. Metode pengambilan keputusan tersebut diisyaratkan sebagai sumber keluhan tertentu; alih-alih mengikuti jalur ‘normal’ dengan berkonsultasi dengan JCR yang lebih luas, Presiden telah mendekati Dewan (yang terdiri dari anggota staf senior) untuk meloloskan reformasi. Rangkaian peristiwa ini diisyaratkan dalam pers mahasiswa sebagai ‘pelanggaran’ proses hukum. Artikel tersebut melaporkan bahwa banyak mahasiswi marah dengan restrukturisasi ini, terutama mengingat rasio laki-laki dan perempuan di kampus tersebut adalah 70:30. Tutor Senior (laki-laki) dilaporkan ‘berharap’ untuk menyatakan bahwa ‘”Churchill College dengan tegas mendukung advokasi untuk kelompok yang kurang beruntung”, tetapi “serikat mahasiswa harus pada dasarnya independen.”‘ (TCS, 12 Februari 2015, hlm. 3).
4.2 Frame 2: Ruang untuk Para Pria
Pembingkaian surat kabar tentang perempuan di Cambridge terwujud dalam edisi kedua berikut: Bagaimana mahasiswi mengalami Universitas sebagai ruang (sosial) . Analisis dari tiga surat kabar mahasiswa difokuskan pada aktivitas olahraga dan perkumpulan minum mahasiswa dan ‘tukar-menukar’; tradisi Cambridge dari dua perkumpulan, atau kelompok, dari perguruan tinggi yang berbeda yang berkumpul. Liputannya meliputi pembubaran perkumpulan, sifat perkumpulan tersebut, dan pembatalan acara baik di Cambridge maupun universitas lain di Inggris. Dalam bingkai ini, sejumlah tema yang saling terkait tampak jelas: kaitan acara sosial ini dengan ‘laddisme’, budaya predator, dan objektifikasi seksual serta penghinaan terhadap mahasiswi.
‘Budaya Anak Laki-laki’
Skandal tentang perkumpulan minum-minum di universitas dilaporkan di tiga surat kabar mahasiswa pada awal masa Michaelmas 2014. TCS merujuk pada pembubaran klub rugbi London School of Economics setelah para anggotanya membagikan selebaran di pekan mahasiswa baru yang berisi referensi misoginis dan homofobik. Menanggapi berita ini, salah seorang pendiri kelompok diskusi gender di St Catherine berkomentar ‘semoga acara ini akan memungkinkan diskusi tentang bagaimana budaya laki-laki diabadikan di universitas. Jika masalah ini tidak ditangani, maka perjalanan yang diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan gender akan memakan waktu lebih lama’ (TCS, 16 Oktober 2014, hlm. 2). Petugas Perempuan (CUSU) berkomentar:
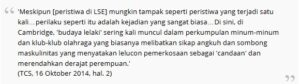
Seorang kolumnis, saat memulai kuliahnya, menggambarkan visinya tentang seperti apa Cambridge nantinya—sebuah ‘lingkungan gotik megah’ tempat minat sejati akan dibahas, tetapi hanya untuk menemukan kegiatan yang menumbuhkan lingkungan ‘berbahaya’ bagi semua jenis kelamin. Penulis berpendapat bahwa pertukaran dan perkumpulan minum-minum tidak hanya ‘merusak’ moral perempuan, tetapi juga sama-sama ‘merugikan’ bagi laki-laki; budaya yang buruk terjadi di mana mahasiswa laki-laki merasa terpaksa untuk bertindak dalam batasan ‘budaya laki-laki’ yang semakin meningkat (Varsity, 28 November 2014, hlm. 14). Di sini kita melihat bagaimana bahasa yang digunakan—berbahaya, merusak, merugikan, mengerikan—dengan jelas memposisikan aspek budaya mahasiswa ini sebagai penyebab kerugian bagi perempuan dan laki-laki. Penggunaan kata sifat yang emosional dan pencantuman kata sifat ini menekankan budaya yang sangat gelap.
Kita juga melihat adanya hubungan antara budaya anak laki-laki dan ‘candaan’. Dalam sebuah wawancara dengan Laura Bates—lulusan Cambridge dan pendiri proyek ‘Everyday Sexism’—analisis konsep ini diajukan; ‘…ini adalah gagasan bahwa semua ini adalah lelucon…[ini] adalah cara yang sangat cerdik untuk membungkam karena menyiratkan bahwa ada lelucon yang melibatkan semua orang’ (TCS, 27 November 2014, hlm. 16). Di sini, penggunaan ‘cara yang cerdik untuk membungkam’ menyiratkan bahwa perempuan tidak memiliki suara karena jika mereka mengeluh, mereka akan dituduh tidak memiliki selera humor.
Pria Predator: Wanita sebagai Mangsa
Yang juga mengejutkan adalah budaya predatoris dan jahat yang melingkupi acara sosial ini. Ambil contoh berikut; pada bulan Oktober, Tab melaporkan rincian ‘Sinster Swap’ Churchill Bulldogs—acara mahasiswa baru perkumpulan itu—yang telah dibatalkan menyusul tuduhan alumni yang datang dari London untuk menghadiri acara yang akan diadakan di rumah sewaan pribadi (saat itu Bulldogs dilarang mengadakan acara di Kampus). Tab melaporkan bahwa pertukaran itu dibuat dengan tujuan ‘mengintai’ pendatang baru perempuan yang naif—setelah berminggu-minggu ‘mengintai’ Facebook—dengan setiap gadis terpilih menerima undangan tulisan tangan yang meminta kehadiran mereka di Pitt Club dengan ‘kebijaksanaan penuh’. Penggunaan kata ‘mengintai’ dan ‘mengintai’ membangkitkan gambaran perempuan yang diburu. Sebagai tanggapan, Tutor Senior di Churchill, mengirim email (dilaporkan secara lengkap dalam liputan pers) ke semua siswa, menasihati mereka agar tidak bergabung dengan perkumpulan minum-minum, yang ia gambarkan sebagai ‘tidak menyenangkan’ dan ‘predator’ (The Tab, Oktober, 2014); ‘saat ini ada kekhawatiran umum di antara serikat mahasiswa di Cambridge dan Inggris Raya serta dunia tentang perilaku predator terhadap mahasiswi muda’. Menyarankan agar siswa tidak bergabung, dan berpartisipasi, dalam perkumpulan minum-minum, ia meminta agar siswa berpikir ‘sangat keras’ tentang bagaimana keanggotaan, atau partisipasi tersebut sesuai dengan kekhawatiran tentang kebencian terhadap wanita dan diskriminasi seksual.
Objektifikasi dan Penghinaan Seksual terhadap Perempuan
Contoh-contoh tentang cara siswi dipermalukan dan diseksualisasikan terlihat jelas sepanjang tahun. Pada awal masa Michaelmas, Varsity melaporkan bahwa perkumpulan minum-minum Emmanuel College—Emmanuel Lions—secara resmi telah dibubarkan. Presiden Lions dilaporkan telah mengirimkan email yang memaparkan daftar inisiasi mahasiswa baru dan jadwal pertukaran, dengan mencatat bahwa daftar pertukaran tersebut dapat berubah ‘tergantung pada permintaan (misalnya permintaan perempuan untuk penis Emmanuel)’ (Varsity, 27 Oktober 2014, hlm. 8). Kembali ke contoh ‘tukar-menukar yang mengerikan’ Churchill Bulldogs, laporan tersebut menjelaskan apa yang diminta untuk dilakukan oleh para siswi tahun sebelumnya: memperkenalkan diri mereka kepada sekelompok pria yang diam sambil menguraikan ‘harapan mereka tentang apa yang akan terjadi malam itu’; berbaris dan mengambil bagian dalam kompetisi membuka kaitan bra yang dilakukan oleh ‘para lelaki tua’ dan minum koktail yang mematikan. Seorang siswa anonim berkomentar, ‘mereka membuat hidup saya benar-benar seperti neraka dengan komentar-komentar mereka yang merendahkan’ (The Tab, Oktober, 2014).
Pada pertengahan tahun 2014, perkumpulan peminum Selwyn—Templar—muncul di media mahasiswa dengan laporan pesan antaranggota yang menilai mahasiswi yang pernah berhubungan seks, dan mendorong yang lain untuk ‘mencicipi’. Pesan selanjutnya mencakup kisah anggota yang bertemu dengan mahasiswi yang tertekan, yang mereka beri tahu bahwa siapa pun yang membawa mahasiswi ini ke kampus harus ‘memperbaiki seleranya’ dan foto mahasiswi yang diunggah dengan komentar seperti ‘apakah dia lupa memakai celana lagi?’ (Varsity 28 November 2014; TCS 4 Desember 2014).
Tahun ajaran 2014/15 berakhir dengan Wyverns—perkumpulan minum Magdalene—membatalkan rencana mereka untuk memperkenalkan kembali gulat jeli di pesta kebun tahunan mereka. The Gentlemen Wyverns dilaporkan telah berusaha meyakinkan kampus mereka bahwa acara tersebut tidak dimotivasi oleh ‘keinginan untuk mengintip wanita berbikini yang diolesi ramuan agar-agar’ (The Tab, Juni 2015) tetapi untuk menghindari kontroversi, kompetisi tersebut akan terbuka untuk kedua jenis kelamin dan karenanya akan ‘bertindak sebagai salah satu dari banyak kegiatan yang konyol dan menyenangkan’. Di sini kita melihat bagaimana sarkasme digunakan untuk meremehkan objektifikasi siswa perempuan. Pada tahun ajaran sebelumnya, Wyvern telah dilaporkan di pers nasional karena berjalan melalui Oxford sambil meneriakkan dan menyanyikan tentang pemerkosaan (The Tab, Mei 2014).
Dalam wawancara dengan Laura Bates (disebutkan sebelumnya), dia membahas lonjakan email yang diterimanya yang merinci malam-malam di klub; ‘para penyanyi rap dan tukang pukul’, ‘para CEO dan pelacur perusahaan’ dan ‘pemain golf dan pelacur tenis’, dengan berkomentar ‘itu adalah fakta bahwa kita tampaknya benar-benar diseksualisasikan di setiap kesempatan yang tidak terjadi pada pria’ (TCS, 27 November 2014, hlm. 16) Merenungkan waktunya di Cambridge, dia ingat merasa sangat malu ketika seorang anak laki-laki melewatinya dan berkata ‘urgh apakah kita boleh memilih yang mana sebelum bertukar?’
4.3 Bingkai 3: Ruang Aman
Pembingkaian surat kabar terhadap perempuan di Cambridge terwujud dalam edisi ketiga berikut: keselamatan perempuan sebagai mahasiswa . Analisis pers mahasiswa memberikan wawasan tentang luasnya kekerasan seksual di Universitas, pengenalan lokakarya persetujuan seksual, dan perdebatan berikutnya, bersama dengan pandangan tentang prosedur Universitas untuk menangani pelecehan dan kekerasan seksual. Bukti dari Inggris dan internasional mendokumentasikan budaya pelecehan seksual di kampus-kampus universitas. Pada awal tahun akademik 2014, pers mahasiswa melaporkan bahwa lebih dari separuh perguruan tinggi telah memperkenalkan lokakarya persetujuan seksual ‘wajib’ untuk mahasiswa baru. Perkembangan ini dilaporkan sebagai hasil dari Kampanye Perempuan CUSU untuk menarik perhatian pada masalah ini (Varsity, 3 Oktober 2014) dan bukti ‘yang menunjukkan kekerasan seksual endemik di kalangan mahasiswa’ (TCS, 6 Oktober 2014). Survei yang dilakukan oleh Varsity pada tahun akademik sebelumnya telah mengungkapkan bahwa 46% dari lebih dari 2000 responden telah diraba-raba saat berada di Cambridge, dengan 8,4% responden perempuan melaporkan menjadi korban percobaan penyerangan seksual, dan 4,4% telah mengalami penyerangan serius. Tema yang muncul dari kerangka ini adalah hubungan antara budaya anak laki-laki dan pelecehan seksual serta peran lokakarya persetujuan seksual.
Budaya Laki-laki = Budaya Pemerkosaan?
Komponen utama budaya pemuda adalah perkumpulan minum-minum dan olahraga; salah satu tema yang dibahas dalam pers mahasiswa adalah sejauh mana konteks ini merupakan ruang seksual yang aman bagi mahasiswi. Pengenalan lokakarya persetujuan seksual dijelaskan oleh petugas Perempuan CUSU sebagai bagian dari tantangan yang lebih luas untuk ‘menangani budaya minum-minum untuk memastikan lingkungan sosial yang aman’ (The Tab, Mei 2014) dan sementara kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang dapat dicap lebih buruk di beberapa universitas daripada yang lain.
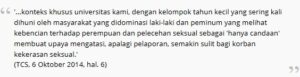
Namun, seorang pemain rugby pria berkomentar bahwa penggunaan istilah ‘budaya pemerkosaan’ saat ini mengandung implikasi bahwa budaya pemuda sama dengan budaya pemerkosaan; ‘bukan berarti masyarakat peminum menganggap boleh memperkosa seseorang, dan dalam hal itu budaya pemerkosaan tidak ada’ (The Tab, Mei 2014). Sebagai tandingan satir terhadap pandangan bahwa masyarakat peminum dan budaya tukar-menukar di Cambridge tidak menyediakan konteks di mana kekerasan seksual dapat terjadi, sebuah artikel berjudul: Pelaku tukar-menukar bermaksud “bukan pemerkosaan” dimulai dengan pernyataan ‘Saya ingin memperjelas…Saya tidak bermaksud memperkosa’ (Varsity, 28 November 2014). Artikel tersebut terus menjelaskan bagaimana mahasiswa akan mengajak mahasiswa baru ke lingkungan yang penuh tekanan, di mana mereka akan mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan:
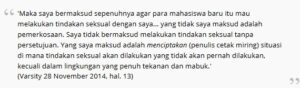
Lokakarya Persetujuan Seksual: Sebuah Langkah Kontroversial
Pengenalan lokakarya persetujuan seksual dilaporkan sebagai hal yang kontroversial. Kontroversi tersebut berfokus pada apakah peningkatan kesadaran tentang persetujuan seksual paling baik dicapai melalui lokakarya wajib (komentar yang dibuat oleh Prof. Mary Beard); bahwa orang-orang yang akan berhubungan seks dengan wanita mabuk, yang tidak dapat memberikan persetujuan, tidak mungkin terpengaruh oleh lokakarya tersebut; bahwa untuk mulai memberi tahu siswa berusia 18 tahun sudah terlambat dan bahwa masalah persetujuan tidak dapat ditangani dalam satu sesi 30 menit, melainkan diperlukan perubahan sosial yang lebih luas. Mahasiswa baru dilaporkan menganggap lokakarya tersebut sebagai ‘menggurui’, ‘tidak perlu’ dan ‘alasan untuk lebih mengebiri siswa laki-laki’.
Pada bulan Mei (Tab, 2015), pers mahasiswa melaporkan bahwa poster Cambridge for Consent dirusak. Laporan tersebut mencatat ‘para pelawak’—individu-individu terkenal dari Trinity—telah mengubah slogan ‘tidak berarti tidak’ menjadi ‘tidak berarti ya’. Seorang petugas wanita berkomentar:

Lokakarya Persetujuan Seksual: Langkah Awal yang Positif
Sebaliknya, sebuah artikel di The Tab (September 2014) yang berjudul ‘kritikus lokakarya persetujuan adalah orang bodoh’, berpendapat bahwa lokakarya memang memberi tahu orang-orang bahwa mereka perlu mengajukan pertanyaan dasar seperti ‘apakah Anda setuju dengan ini?’ dan ‘apakah Anda ingin kami melakukannya lebih lambat’. Membahas keberatan yang diajukan, penulis berpendapat bahwa ada dasar umum untuk keberatan tersebut – mengabaikan masalah dan/atau tidak menganggapnya dapat diperbaiki dengan pendidikan:
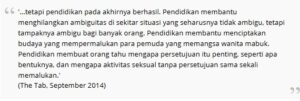
Pada bulan November, Tab menerbitkan sebuah artikel berjudul ‘Lokakarya Persetujuan: Perspektif Korban’ di mana seorang siswa merenungkan pengalamannya memimpin sebuah lokakarya sebagai ‘korban pemerkosaan’; kata-kata, tulisnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, lokakarya persetujuan tersebut berfungsi untuk mengingatkannya tentang keabsahan dari apa yang telah terjadi padanya , memberinya suara atas pengalamannya, memberdayakannya dalam pemulihannya, dan menyediakan ruang . membuka percakapan tentang semua aspek seks untuk semua orang. Penulis berkomentar bahwa lokakarya semacam itu mungkin tampak seperti langkah yang sangat kecil, tetapi langkah-langkah kecil lebih baik daripada tidak sama sekali; lokakarya ‘memberikan suara kepada setiap orang untuk mengatakan tidak’ (The Tab, November, 2014).
Penulis perempuan lain yang juga membantu dalam lokakarya persetujuan seksual merenungkan mahasiswa baru laki-laki yang tersinggung dengan gagasan bahwa persetujuan seksual diajukan sebagai masalah perempuan, dengan laki-laki dipandang sebagai pelaku, meskipun faktanya salah satu ‘mitos’ yang dibahas dalam lokakarya tersebut adalah bahwa hanya perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual. Penulis berpendapat bahwa perempuan tidak berusaha menyalahkan laki-laki; ‘dalam istilah yang paling sederhana, secara historis… seluruh struktur dunia kita telah didasarkan pada gagasan tertentu tentang bagaimana menjadi manusia yang, sejak zaman Aristoteles, telah memandang perempuan sebagai bawahan’. Ia melanjutkan dengan menekankan:
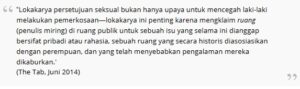
Di sini kita melihat bagaimana penulis ini menggunakan wacana klaim ruang publik untuk menyuarakan apa yang secara tradisional menempati ruang privat.
5 Diskusi: Ruang yang Diperebutkan
Mari kita kembali ke pertanyaan penelitian utama Purwar (2004): apa yang terjadi ketika tubuh-tubuh yang tidak diharapkan menempati tempat-tempat tertentu melakukannya? Dan apa syarat-syarat koeksistensi? Kita telah melihat bahwa mahasiswi di Cambridge telah dikecualikan dari ruang-ruang yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Pitt Club, misalnya, bukan hanya metafora, tetapi representasi fisik dari ‘klub laki-laki’, yang telah menjadi aspek kehidupan universitas di Cambridge yang diterima dan dinormalisasi hingga saat ini. Sebagai tubuh yang secara historis tidak menghuni ruang publik ini, kita telah menyaksikan berbagai masalah yang berkaitan dengan politik suara (Aiston 2021 ) dan perjuangan perempuan untuk didengar di ruang ini, misalnya, marginalisasi mereka dalam berbicara di depan umum dan kesenjangan pencapaian dalam History Tripos. Kita juga telah melihat bagaimana tubuh perempuan dapat disingkirkan dari ruang-ruang publik yang penuh kekuasaan, misalnya, pencopotan posisi kepemimpinan petugas perempuan di Churchill.
Penelitian menunjukkan bahwa ‘budaya lad’, atau perilaku ‘laddish’ yang melibatkan minum berat, bersama dengan perilaku seksis dan mengintimidasi, saat ini membentuk fondasi bagi hegemoni maskulinitas yang dipraktikkan oleh banyak mahasiswa pria (Dempster 2009 , 2011 ). Kampanye yang mengejek dan menantang untuk mengatasi misogini itu sendiri juga merupakan pertunjukan kelaki-lakian (Jeffries 2019 ); penodaan poster Cambridge for Consent oleh ‘pelawak’ terkenal dari Trinity adalah contohnya. Budaya ‘lad’ diposisikan sebagai serangkaian praktik sosial yang bermasalah dan berbahaya dalam pers mahasiswa, yang direpresentasikan dalam istilah monolitik, dengan sedikit ‘repertoar’ yang bertentangan (Owen 2020 ).
Laddisme kontemporer telah diartikulasikan sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah—atau ruang —yang secara tradisional maskulin melalui seksisme dan kekerasan (Phipps 2017 ). Para pelaku utama di Inggris telah diidentifikasi sebagai pria kulit putih kelas menengah; pemain rugby, anggota masyarakat peminum dan debat dari universitas-universitas elit. Dalam konteks Universitas Cambridge, kita melihat peran masyarakat peminum dan ‘tukar-menukar’ dalam melestarikan budaya semacam itu. Di AS, maskulinitas elit dapat dilihat dalam perkumpulan mahasiswa:

Sebagai bentuk baru dari seksisme, laddisme dapat dilihat sebagai respon defensif terhadap kesuksesan yang dirasakan oleh perempuan, dan terdapat banyak penelitian yang menggambarkan bagaimana seksisme dan pelecehan seksual berfungsi untuk memungkinkan laki-laki mendapatkan kembali kekuasaan dan ruang dalam pendidikan tinggi (Phipps dan Young 2015). ). Dan aspek utama dari perebutan kembali kekuasaan dan ruang adalah untuk menjadikan tubuh perempuan sebagai objek seksual dalam ruang tersebut, dan sebagai hasilnya, meminggirkan tubuh perempuan sebagai intelektual dalam ruang intelektual.
Kita mungkin mempertimbangkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme untuk melanggengkan dikotomi publik/pribadi, sehingga perempuan yang melanggar biner spasial dan memasuki ruang publik harus berjuang melawan rasa takut yang terinternalisasi terhadap kekerasan laki-laki (Doan 2010 ). Pada bulan Maret 2015, TCS melaporkan tentang ‘Reclaim the night’—pawai yang berasal dari tahun 1977 ketika polisi menyarankan perempuan untuk menghindari berjalan di jalan pada malam hari selama masa kekuasaan Yorkshire Ripper. Dilaporkan sebagai respons yang sangat dibutuhkan terhadap pembatasan yang dikenakan pada perempuan, dan pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada korban kekerasan seksual, penulis TCS membela prinsip pengecualian (TCS, 5 Maret 2015); ‘Bagi perempuan untuk berbaris bersama tanpa laki-laki adalah merebut kembali ruang (penulis miring) kekerasan laki-laki membuat tidak aman bagi mereka’.
Seperti yang dikemukakan oleh salah satu penulis Varsity, pengecualian dari luar angkasa atas dasar gender adalah wacana yang rumit:

Menariknya, kita dapat melihat bagaimana wacana ruang dimanfaatkan. Kita juga dapat melihat bukti ruang yang diciptakan perempuan di Cambridge untuk mempersiapkan diri memasuki dan menghuni ranah publik secara spasial; misalnya, lokakarya berbicara di depan umum bagi perempuan (Varsity, 3 Oktober 2014). The Tab melaporkan perdebatan ‘berat’ yang dipicu oleh iklan lokakarya tersebut, dengan pengecualian laki-laki dari lokakarya tersebut yang dipertanyakan. Sebagai tanggapan, Petugas Pers laki-laki untuk Cambridge Union dilaporkan berkomentar ironis: ‘mereka (laki-laki) memiliki ruang mereka sendiri. Itu dimulai sekitar 4000 SM dan berlangsung selama beberapa saat’ (The Tab, April 2014).
Wacana seputar pendidikan tinggi yang difeminisasi gagal mengenali bahwa meskipun perempuan sebagai mahasiswa mungkin secara statistik diuntungkan—51% mahasiswa di Cambridge adalah perempuan pada tahun 2024 (HESA)—secara kualitatif, mereka tetap dirugikan. Secara khusus, kelompok status yang kuat mempertahankan dominasi kualitatif sebagai hasil dari otoritas dan keuntungan yang lebih luas dan bahwa partisipasi dalam pendidikan tinggi perlu dipahami dalam konteks rezim gender yang lebih luas (Woodfield 2019) ). Seperti yang dikomentari oleh seorang penulis:
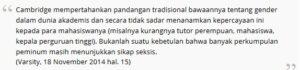
Namun, pers mahasiswa Universitas Cambridge telah memberikan bukti agensi mahasiswa terkait dengan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual, bersamaan dengan tantangan terhadap norma gender. Meningkatnya aktivitas feminis mahasiswa terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual (Phipps dan Young, 2014b). Penelitian menunjukkan bahwa aktivisme mahasiswa akar rumput telah menghasilkan kampanye khusus dalam konteks Inggris untuk meningkatkan kesadaran dan memerangi misogini, berbeda dengan tanggapan institusional, yang ‘ragu-ragu’ karena takut reputasinya rusak (Jeffries 2019 ). Ruang perlawanan telah dibentuk: ‘meskipun universitas baru-baru ini menjadi sorotan karena kasus seksisme, universitas juga dapat menyediakan lingkungan yang subur untuk perlawanan terhadap seksisme’ (Lewis et al. 2018 ).
Bukti dari pers mahasiswa menunjukkan bahwa Universitas Cambridge bukanlah ruang (sosial) yang difeminisasi. Penting untuk mengakui bahwa meskipun pers mahasiswa berusaha mendefinisikan apa artinya menjadi mahasiswa di Cambridge, pers tersebut tidak mewujudkan keseluruhan pengalaman tersebut. Meskipun demikian, pada tahun akademik 2014–2015 di mana kita menyaksikan peningkatan perhatian internasional dari para akademisi, media, dan universitas, bersamaan dengan diperkenalkannya lokakarya persetujuan seksual di Universitas Cambridge, jelas bahwa meskipun perempuan tidak lagi ‘tidak pada tempatnya’ (Aiston 2006 ), mereka menghuni ruang yang diperebutkan .
6 Kesimpulan
Artikel ini menyajikan analisis pers mahasiswa pada tahun akademik 2014–2015. Ada bukti yang menunjukkan bahwa isu yang diangkat terus menjadi sangat relevan dan, seperti dicatat dalam diskusi, tidak unik bagi Universitas Cambridge. Pada September 2020, Universitas Durham menjadi berita utama dengan laporan tentang ‘budaya pemuda’ di mana forum minggu pertama mendorong kontes di antara ‘pemuda mewah’ untuk tidur dengan gadis ‘termiskin’ (The Times 2020 ). Pada tahun 2022, Cambridge terus membuat pers nasional. Artikel ‘Perkumpulan minum ” Predator” (penulis miring) dikutuk oleh kepala perguruan tinggi’ (The Times 2022 , hlm. 12), mendokumentasikan kritik Master of Downing College terhadap perkumpulan minum ‘Gentleman Patricians’, yang mengirim undangan eksplisit dan ‘predator’ kepada wanita. Bahasa Indonesia: Dalam sebuah artikel berjudul ‘Mengapa 1972 merupakan tahun yang lebih baik untuk menjadi seorang wanita daripada 2022’ (The Sunday Times 2022 ), Dorothy Byrne, Presiden Murray Edwards College, Cambridge, merefleksikan pelecehan seksual terhadap wanita dengan berkomentar ‘seorang mahasiswa mengatakan kepada saya bahwa pelecehan sangat umum terjadi, mereka bahkan tidak repot-repot membicarakannya’ (The Times 2022 , hlm. 27). Sementara itu, pers mahasiswa Universitas Cambridge terus mengangkat isu-isu yang telah dibahas di seluruh artikel ini. Misalnya, dalam edisi akhir Januari Varisty (21 Januari 2022) tajuk utama surat kabar tersebut adalah ‘Dating app dons’, sebuah laporan yang mendokumentasikan akademisi senior Cambridge yang mencocokkan dan mengirim pesan kepada mahasiswa sarjana di aplikasi kencan Tinder, diikuti oleh bagian komentar yang menyatakan bahwa Universitas tidak boleh menutup-nutupi klaim terhadap para don. Edisi yang sama juga melaporkan bahwa pria kulit putih terdiri dari 70% pembicara debat untuk masa Prapaskah. Pada tahun 2023, TCS membahas kesenjangan gender dalam tripos STEM, yang mana perempuan cenderung tidak mendapatkan penghargaan pertama, sementara pada saat penulisan, Varsity menulis tajuk utama dengan ‘Mari kita berhenti berpura-pura bahwa masyarakat peminum dapat bersikap inklusif’. Ditulis oleh seorang perempuan kulit berwarna, penulis merefleksikan sifat regresif dari pertukaran universitas di mana perempuan ‘terikat’ dengan seorang laki-laki dan pada dasarnya didorong untuk ‘berteman’ dengan seseorang.
Berdasarkan penelitian karya Puwar yang berkaitan dengan staf kulit berwarna sebagai penyerbu ruang di akademi, artikel ini menyediakan kerangka kerja untuk mempertimbangkan bagaimana mahasiswi dapat mengalami universitas sebagai ‘ruang’ melalui media pers mahasiswa. Suara mahasiswa sebagian besar telah digunakan dalam pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas dan pengembangan profesional yang terkait dengan pembelajaran dan pengajaran. Seperti yang ditekankan McLeod ( 2011 ), memberikan perhatian pada suara mahasiswa dapat menjadi pengakuan yang berharga atas sudut pandang dan pengalaman mahasiswa. Menganalisis suara mahasiswa melalui media pers mahasiswa menghadirkan dimensi alternatif baru pada karya EDI. Analisis bingkai, tema, dan wacana memberi kesempatan bagi universitas untuk mendengarkan suara mahasiswa dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana universitas menanggapi suara mahasiswa dan siapa yang memikul tanggung jawab untuk mendengarkan dan berubah? (McLeod 2011 ). Tentu saja, perhatian harus diberikan pada suara siapa yang diistimewakan. Tentu saja, tahun ketika lokakarya persetujuan seksual diperkenalkan di Cambridge, suara-suara itulah yang berbicara dan menyuarakan tentang kesetaraan gender yang paling menonjol. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua artikel yang terkait dengan gender dan identitas penting lainnya yang saling bersinggungan ditelusuri. Namun, suara ‘perempuan’ sebagai identitas pemersatulah yang diistimewakan dalam tahun akademik 2014–2015. Menariknya, fokus pada pelecehan seksual sudah ada sebelum tahun 2017, ketika tagar #MeToo menjadi viral. Selain itu, hal ini sudah ada sebelum protes Black Lives Matter terbesar dan paling meluas dalam sejarah gerakan tersebut, setelah pembunuhan George Floyd pada tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan lebih baru-baru ini, melalui media pers mahasiswa, bagaimana kelompok mahasiswa terpinggirkan lainnya mengalami universitas sebagai ruang (sosial), dengan memberikan perhatian khusus pada interseksionalitas dan sejauh mana suara-suara ini hadir dan didengar.
